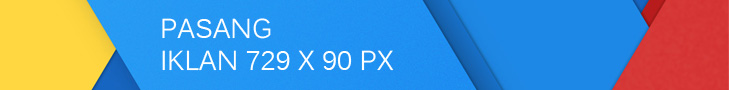DALAM khazanah budaya Sunda, terdapat peribahasa yang tampak sederhana namun menyimpan kedalaman makna yang luar biasa, yakni “kurung batok”. Ia bukan sekadar ungkapan harfiah tentang tertutupnya seseorang di bawah batok kelapa, melainkan sebuah cerminan keadaan batin manusia—yang hidup dan berpikir dalam ruang sempit, tertutup dari cakrawala pengetahuan yang lebih luas, dan terkunci dalam lingkaran sempit keyakinan, kebiasaan, atau pengalaman yang tak pernah diperbarui.
Peribahasa ini mengisyaratkan pada terbatasnya wawasan, ketakutan pada perbedaan, dan penolakan terhadap hal-hal baru. Seperti katak dalam tempurung, seseorang yang “kurung batok” mengira dunia hanyalah seluas ruang pandangnya, padahal kenyataan jauh melampaui apa yang bisa ia lihat, dengar, atau pahami.
Di balik peribahasa ini tersimpan kritik kultural terhadap kejumudan, yaitu kondisi di mana seseorang atau kelompok merasa cukup dengan apa yang dimiliki: cara berpikir lama, sistem nilai lama, dan identitas lama—semua dijaga dan dilanggengkan bukan karena kebenaran, tapi karena kenyamanan dan rasa aman. Mereka tidak membuka diri untuk berdialog, tidak bersedia dikritik, dan alergi terhadap perubahan. Dalam konteks sosial-budaya, ini adalah gejala stagnasi intelektual dan isolasi sosial.
Namun, di zaman modern, bentuk “kurung batok” tidak lagi berupa keterisolasian fisik, melainkan pengurungan digital dan ideologis. Media sosial, algoritma, dan dunia informasi yang terkurasi sering menjadikan kita hidup dalam versi modern dari tempurung: hanya mendengar suara-suara yang kita sukai, berinteraksi dengan orang-orang yang berpandangan serupa, dan menghindari perbedaan yang menantang pola pikir kita.
Tanpa disadari, kita bisa menjadi pribadi yang “kurung batok digital”: merasa paling benar, tidak mau mendengar, menolak belajar dari orang lain, dan anti terhadap kompleksitas. Dalam psikologi sosial, ini berkaitan erat dengan cognitive dissonance (kecanggungan batin saat dihadapkan dengan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan kita), dan kita menyelesaikannya dengan menyangkal informasi tersebut atau menjauhi sumbernya.
Secara lebih dalam, kondisi ini menyumbang pada inferioritas terselubung: karena tidak pernah mengasah diri untuk berinteraksi dengan pandangan yang berbeda, maka ketahanan nalar dan emosional kita rapuh. Kita mudah tersinggung, mudah menghakimi, dan cepat menyimpulkan salah—semua karena kita terbiasa hidup dalam tempurung yang sempit dan tidak terbiasa dengan semesta wacana yang luas.
Di pihak lain. Di tengah derasnya arus informasi hari ini, kita dihadapkan bukan pada kelangkaan kebenaran, tetapi pada keengganan menghadapinya. Bukan karena kebenaran bersembunyi, melainkan karena kita sering memilih untuk bersembunyi dari kebenaran. Dunia digital modern membentuk ruang-ruang gema yang memperkuat pandangan sendiri dan mengabaikan kritik yang mencerahkan.
Secara psikologis, echo chamber adalah ruang kognitif dan sosial yang tercipta ketika seseorang hanya dikelilingi oleh orang-orang atau informasi yang menyetujui pandangannya. Dalam ruang ini, keberagaman perspektif ditiadakan, sehingga opini pribadi dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Sosiolog menyebutnya sebagai bentuk homogenitas sosial yang ekstrem, yang memupuk fanatisme, intoleransi, dan resistensi terhadap kritik.

Kondisi ini menciptakan kepercayaan diri yang palsu. Semakin sering seseorang mendengar ulang pendapat yang sama dari lingkaran yang terbatas, semakin besar ia merasa benar. Dalam psikologi, ini membentuk loop penguatan diri ( self-reinforcing loop ), yang pada akhirnya menumpulkan daya nalar kritis dan menumbuhkan arrogant ignorance —ketidaktahuan yang sombong.
Rasulullah ﷺ telah memperingatkan bahwa kebenaran tidak akan hadir dalam jiwa yang menolak untuk mendengarkan dan terbuka:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»
“Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.” (HR. Muslim)
Dari perspektif psikologi media, filter bubble adalah bentukan dari sistem algoritma digital yang hanya menyajikan informasi yang cocok dengan perilaku dan preferensi kita. Secara sosiologis, ini adalah hasil dari personalisasi ekstrem, di mana individu dikurung dalam dunia buatan yang menyesuaikan kenyamanan, bukan kebenaran.
Kita diberi informasi yang ingin kita dengar, bukan yang perlu kita tahu. Akibatnya, pembelajaran sosial terhenti, kemampuan empati menurun, dan pemahaman atas realitas sosial menjadi sempit. Fenomena ini memperkuat bias, memperlemah dialog, dan membentuk masyarakat yang saling mencurigai karena hidup dalam narasi yang saling meniadakan.
Padahal Allah memuliakan orang-orang yang tidak hanya mendengar, tetapi memilih dan mengikuti yang paling baik dari berbagai pandangan:
ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۚ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ
“(Ialah) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal (ulul albab).” (QS. Az-Zumar: 18)
Secara psikologis, confirmation bias adalah kecenderungan untuk menerima informasi yang mendukung pandangan kita, dan menolak informasi yang bertentangan, meskipun faktual. Bias ini memperkuat kepercayaan yang sudah ada, sekaligus menolak pertumbuhan intelektual.
Dalam konteks sosiologis, ini adalah bentuk filter ideologis internal—bukan karena disodorkan sistem, melainkan karena manusia ingin merasa nyaman dengan keyakinannya. Ia menyeleksi bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan selera dan kenyamanan.
Sikap ini membuat manusia rentan terhadap manipulasi politik, polarisasi sosial, dan radikalisasi pemikiran. Mereka lebih senang mendengar apa yang ingin mereka dengar daripada apa yang harus mereka pahami. Padahal, kebenaran sering datang dalam bentuk yang tidak menyenangkan hati, tetapi menyelamatkan nurani.
Allah memperingatkan manusia untuk tidak mengikuti sangkaan semata:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.” (QS. Al-Hujurat: 12)
Dalam tradisi Islam, pribadi yang tidak terperangkap dalam bias dan gelembung adalah ulul albab—orang-orang yang jernih akalnya, lembut hatinya, dan terbuka pikirannya. Mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga rendah hati secara spiritual.
Mereka menyimak setiap pandangan, bukan untuk menyerang atau membantah, tapi untuk mencari kebenaran yang lebih luhur. Mereka berani tidak nyaman, demi membebaskan diri dari jebakan kognitif dan sosial yang memperdaya.
ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ
“Allah adalah cahaya langit dan bumi…” (QS. An-Nur: 35)
Mereka inilah yang hatinya siap menerima cahaya petunjuk itu. Mereka tidak hanya terpapar informasi, tapi juga terbimbing olehnya menuju perubahan diri.
Di tengah hiruk-pikuk wacana, kita perlu bertanya pada diri: apakah kita benar-benar mencari kebenaran, atau hanya ingin menguatkan pendapat sendiri? Apakah kita membangun pikiran, atau sekadar memperkeras gema?
Kebenaran bukan apa yang menyenangkan hati, tapi yang membersihkan jiwa. Ia tidak tumbuh dalam kebisingan yang saling membenarkan, tapi dalam keheningan yang jujur kepada nurani.
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلۡأَبۡصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ
“Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.” (QS. Al-Hajj: 46)
Mari belajar mendengar yang berbeda, mencintai yang benar, dan membebaskan diri dari jeruji gema. Karena cahaya kebenaran, selalu menanti jiwa yang berani menembus kabut kebiasaan. (ADS)