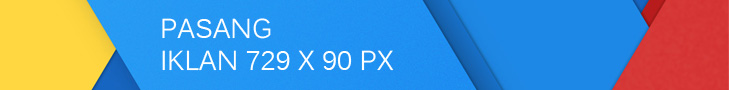Obat Hati
Oleh Dr. Muhammad E. Fuady, M.Ikom (Dosen Fikom Unisba & Pengamat Komunikasi Politik)

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
“ALLAH adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah ceruk yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Minyaknya hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa saja yang Dia kehendaki.”(QS. Al-Nur [24]: 35)
Ayat ini dikenal luas sebagai ayat cahaya. Bukan sekadar karena keindahan metaforanya, tetapi karena kedalaman makna yang dikandungnya. Al-Qur’an tidak sedang menjelaskan cahaya dalam pengertian fisik semata, melainkan cahaya dalam makna hakiki, yakni petunjuk, kebenaran, dan pembimbingan Ilahi dalam kehidupan manusia.
Cahaya yang dimaksud ayat ini bukanlah cahaya yang ditangkap pancaindra. Cahaya matahari, bulan, atau lampu tidak otomatis menjadikan seseorang mampu melihat. Orang buta tetap tidak dapat menangkap cahaya, betapapun terang sinar di hadapannya. Seseorang yang mengalami gangguan mata, seperti ablasio retina pun tidak mampu melihat dengan baik meskipun cahaya tersedia. Dengan kata lain, keberadaan cahaya tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menerima cahaya.
Di sinilah perbedaan mendasar antara cahaya fisik dan cahaya Ilahi.
Imam Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya Misykāt al-Anwār, memaknai ayat cahaya bukan sekadar sebagai metafora, tetapi sebagai kunci untuk memahami hakikat wujud dan hubungan makhluk dengan Allah. Menurutnya, satu-satunya cahaya yang benar-benar hakiki hanyalah Allah. Segala sesuatu selain-Nya disebut cahaya hanya secara kiasan, karena keberadaannya sepenuhnya bergantung kepada-Nya. Cahaya indrawi, cahaya akal, cahaya ilmu, bahkan cahaya ruhani hanyalah pantulan dan pinjaman dari Cahaya Hakiki itu sendiri.
Dalam kerangka ini, Al-Ghazali menautkan istilah nur dengan wujud. Semua makhluk pada hakikatnya “gelap”, dan menjadi “tampak” hanya sejauh disinari oleh wujud Allah. Tanpa cahaya-Nya, tidak ada yang benar-benar terlihat, dipahami, atau bermakna.
Al-Ghazali menafsirkan simbol-simbol dalam ayat cahaya secara mendalam. Misykat dipahami sebagai indera, misbah sebagai akal, zujajah sebagai hati, dan minyak zaitun sebagai daya batin yang murni. Cahaya bertingkat-tingkat itu menggambarkan perjalanan manusia dari penglihatan indrawi, imajinasi, akal, hingga intuisi dan ma’rifat. Frasa “minyaknya hampir menyala walaupun tidak disentuh api” ia pahami sebagai daya nubuwwah. Artinya, cahaya Ilahi tetap bersinar meskipun ditolak, disangkal, atau disalahpahami oleh manusia.
Dengan kata lain, semakin bening “kaca” hati, semakin sempurna cahaya Ilahi memantul di dalamnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap mengandalkan pancaindra dan akal. Namun keduanya memiliki keterbatasan. Indra bisa keliru. Akal pun bisa bias, terutama ketika dipenuhi prasangka. Kita sering menyaksikan bagaimana stereotip bekerja. Dalam isu penghinaan etnis yang sedang booming saaat ini, orang Sunda dianggap lemah dan licik padahal gaya komunikasinya menjunjung kesantunan dan kehati-hatian menjaga perasaan. Akal yang dipenuhi prasangka mudah terkelabui dan menilai secara keliru.
Karena itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa alat utama untuk menerima cahaya kebenaran bukan indera dan bukan semata akal, melainkan hati yang bening. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari).
Hati diibaratkan seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia mampu menangkap dan memantulkan cahaya. Namun jika kotor, berdebu, atau berkarat, cahaya sekuat apa pun tidak akan tertangkap dengan baik. Begitulah hati manusia. Hati yang bening mudah menerima petunjuk. Hati yang kusam sulit membedakan kebenaran.
Almarhum Prof. Djawad Dahlan pernah menyampaikan bahwa hati manusia adalah alat penentu kebenaran. Dalam situasi galau dan dilema, manusia sejatinya dapat bertanya pada hati nuraninya. Namun pertanyaannya, apakah hati masih jernih ataukah sudah tertutup oleh ambisi, kepentingan, dan ego.
Tradisi Islam menawarkan jalan membeningkan hati melalui riyadoh, latihan spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Kearifan ini terekam indah dalam tembang Tombo Ati karya Sunan Bonang: membaca Al-Qur’an dan maknanya, menjaga shalat malam, berkumpul dengan orang-orang saleh, menahan hawa nafsu melalui puasa, dan memperbanyak zikir.
Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan proses membersihkan “kaca” alias bening hati. Membaca Al-Qur’an melatih kesadaran makna. Shalat malam melatih keheningan dan kejujuran diri. Berteman dengan orang saleh membangun ekosistem moral. Puasa menundukkan ego. Zikir menjaga kesadaran kehadiran Tuhan.
Di tengah dunia yang semakin bising, penuh distraksi, dan sarat prasangka, kebutuhan akan hati yang bening menjadi semakin mendesak. Cahaya Allah selalu ada. Persoalannya bukan pada ketiadaan cahaya, melainkan pada kesiapan hati untuk menerimanya.
Cahaya di atas cahaya bukan janji kosong. Ia hadir bagi siapa saja yang bersedia membersihkan cermin hatinya. Dan dari hati yang bening itulah lahir kejernihan berpikir, kedewasaan bersikap, serta kebijaksanaan dalam memandang sesama manusia.**