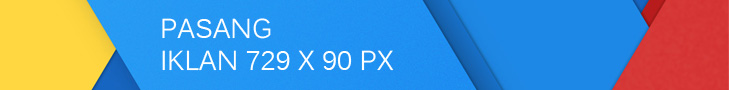Dari Srimulat, Stand Up, Hingga Humor Profetik
Dr. Muhammad E Fuady, M.Ikom (Pengamat Komunikasi dan Dosen Fikom Unisba)

ADA satu kenangan masa kanak-kanak di era 1980-an. Pada malam hari, ketika anak-anak semestinya sudah terlelap, televisi hitam putih masih menyala. Dari layar TVRI, tampil sekelompok pelawak dengan gaya khas, celetukan nyeleneh, dan lagu-lagu yang dipelesetkan seenaknya. Bengawan Solo dipenggal liriknya. Komedi yang terkesan receh, tetapi sukses mengundang gelak tawa.
Di situlah pertama kali terdengar kalimat legendaris, “Hil yang mustahal”, khas Asmuni. Sebuah plesetan sederhana dari “hal yang mustahil”, tetapi terasa sangat lucu, sangat hidup, dan sangat Srimulat.
Komedi Srimulat tidak pernah rumit. Kadang hanya jatuh terduduk karena kursi tak pas. Atau tiba-tiba selonjoran karena kursinya licin. Ada pula adegan menangis yang dikira sedih, padahal ternyata kakinya terinjak.
Kelucuan itu tidak bergantung pada dialog panjang, melainkan pada gesture, atribut, ekspresi tubuh, timing, dan kepolosan. Penonton tidak perlu berpikir keras untuk tertawa, tetapi langsung larut dalam suasana.
Sekitar 1996, lawakan yang sama kembali hadir di layar kaca televisi swasta. Meskipun materinya masih itu-itu saja, ia tetap dinanti. Tidak terasa membosankan, apalagi basi.
Beberapa ikon mereka pun abadi dalam ingatan. Ketika ditanya siapa namanya, ia menjawab lantang, “Bambaaaaang”, dengan mulut mangap terbuka lebar.
Yang lain menyebut namanya, “Paulllll”, sambil menjulurkan lidah panjang, membuat penonton meledak tertawa.
Lalu ada Gogon, dengan potongan rambut nyentrik dan pose tangan bersilang di dada. Hingga kini, masih terasa lucu.
Bahkan jauh setelah masa itu berlalu, komedi Srimulat tidak benar-benar pergi. Andre Taulany dan komedian lain masih kerap menirukan gaya lawakan Srimulat. Polanya sama, tetapi tetap menghibur.
Srimulat tampil apa adanya: komedi ringan, tidak rumit, dan diterima oleh berbagai kalangan. Lawakan semacam ini kini mulai langka di tengah booming komika atau stand up comedian, yang humornya sering dinilai sinis, satir, bahkan berada di “pinggir jurang”. Namun Srimulat tidak pernah benar-benar hilang.
Srimulat menunjukkan bahwa komedi tidak harus canggih. Ia bisa lahir dari keseharian, sederhana tetapi membekas, tidak menua, dan tak lekang oleh waktu.
Dari Srimulat ke Stand Up Comedy
Komedi kemudian bergerak mengikuti generasi. Jika Srimulat bertumpu pada slapstick dan humor fisik, stand up comedy hadir dengan wajah yang berbeda. Humor tidak lagi sekadar soal jatuh, terpeleset, atau salah duduk. Humor dikelola sebagai gagasan dan kritik. Pada titik tertentu, ia menjadi bahasa perlawanan yang halus, tetapi mengusik kekuasaan.
Di sini, tawa tidak hanya muncul karena gesture tubuh, melainkan karena kejelian membaca realitas. Stand up mengajak audiens bukan sekadar tertawa, tetapi juga menyadari situasi sosial-politik yang tengah berlangsung.
Salah satu contoh menarik adalah ketika Pandji Pragiwaksono menggelar pertunjukan dengan tajuk Mens Rea.
Bagi masyarakat non-hukum, istilah mens rea terdengar asing. Publik mulai mengenalnya lewat perdebatan antara mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dan Feri Amsari di televisi terkait perkara Tom Lembong, ketika unsur niat batin menjadi titik krusial dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.
Secara sederhana, mens rea berarti niat batin, yang kerap diterjemahkan sebagai niat jahat dalam melakukan suatu perbuatan.
Istilah ini kemudian masuk ke ruang budaya populer. Melalui panggung komedi, Pandji mengajak publik melakukan refleksi tentang niat, kekuasaan, dan tanggung jawab para elite, pembuat kebijakan, serta pejabat negara.
Tidak semua orang menyukai komedi ala komika. Masih banyak penikmat komedi slapstick, komedi situasi, atau humor fisik yang sederhana. Tidak semua orang pula menyukai Pandji. Namun Mens Rea justru membincangkan tema “power tends to corrupt” melalui humor dan satire.
Apakah sebuah komedi terasa lucu atau tidak sangat ditentukan oleh konteks, audiens, dan frekuensi makna. Humor bekerja efektif ketika berada pada frekuensi yang sama dengan pendengarnya. Saat audiens memiliki latar pengetahuan, sensitivitas, dan horizon makna yang relatif serupa, humor menjadi ruang dialog yang cair. Tawa muncul karena ada kesepahaman diam-diam dan arbitrer antara pembicara dan pendengar.
Namun ketika frekuensi itu berbeda, humor bisa berubah menjadi horor. Bagi penguasa, elite, atau institusi yang disinggung, humor dapat dibaca sebagai pesan yang mengganggu, bahkan menakutkan. Bagi komika sendiri, komedi bisa berubah menjadi beban ketika kritik yang disampaikan dianggap sebagai penghinaan.
Dalam masyarakat yang terpolarisasi, humor kehilangan pijakan sosialnya. Ia tidak lagi berada di ruang aman, melainkan di medan sensitif yang penuh kecurigaan. Kritik yang diniatkan baik melalui komedi dapat ditafsir penguasa sebagai niat jahat.
Humor Profetik
Humor sejatinya bukan hal asing dalam tradisi Islam. Beberapa riwayat menunjukkan Rasulullah SAW bercanda, tersenyum, bahkan tertawa, tetapi selalu berada dalam koridor kebenaran dan keteladanan. Humor beliau tidak pernah merendahkan martabat orang lain, tidak melukai, dan tidak pula mengandung dusta. Justru di situlah letak kekuatannya, humor menjadi medium komunikasi yang hangat, edukatif, dan membekas. Sabda Nabi, “Aku bercanda tapi tidak berkata kecuali yang benar” (HR Tirmidzi).
Salah satu kisah yang kerap dikutip adalah ketika seorang nenek datang kepada Rasulullah SAW dan meminta didoakan agar masuk surga. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mengejutkan, “Surga tidak dimasuki oleh nenek tua.” Mendengar itu, sang nenek menangis dan pergi. Namun Rasulullah segera menjelaskan maksud ucapannya bahwa semua penghuni surga akan dikembalikan pada usia muda. Candaan itu bukan untuk menipu atau menyakiti, melainkan untuk membuka ruang pemahaman baru dengan cara yang ringan dan mengena.
Humor Nabi juga tampak dalam keseharian bersama para sahabat. Dalam satu riwayat, Ali makan kurma bersama Nabi. Menantu Nabi ini meletakkan sebagian biji-biji kurma sisa kurma yang dimakannya di samping Nabi Muhammad, seolah biji-biji kurma itu merupakan sisa Nabi Muhammad SAW. “Ya Rasul, aku tidak menyangka Rasul menyukai kurma, hingga begitu banyak engkau memakannya,” ujar Ali Bin Abi Tholib, “Aku tidak selapar dan selahap engkau, Ali”, kata Nabi Muhammad.
“Terbukti engkau memakan kurma dengan biji-bijinya hingga kurma-kurma yang engkau makan tak bersisa dengan bijinya”, tambah Nabi. Candaan sederhana ini memancing tawa dan keakraban, sekaligus menunjukkan sisi manusiawi Rasulullah sebagai nabi, mertua, dan pemimpin yang hangat, tidak berjarak, dan empatik
Kita juga mengenal Nu’aiman, sahabat Nabi yang terkenal dengan kelakuan isengnya. Canda Nu’aiman terbilang ekstrem, seperti menjual sahabat sebagai budak untuk bercanda atau membuat ulah yang merepotkan. Namun Rasulullah tidak merespons dengan kemarahan, melainkan dengan tawa yang sampai memperlihatkan gigi gerahamnya. Dalam konteks komunikasi, ini menunjukkan bahwa humor bisa menjadi cara merawat relasi sosial, bahkan ketika berhadapan dengan perilaku yang menjengkelkan.
Tokoh lain yang sering dipersepsikan kaku adalah Umar bin Khattab. Namun riwayat menunjukkan bahwa Umar pun tidak asing dengan tawa. Humor reflektif juga tampak dalam kisah Umar bin Khattab sendiri, bahkan ketika ia menertawakan masa lalunya. Dalam satu riwayat yang sering diceritakan ulang oleh para ulama, Umar pernah berkisah tentang pengalamannya di masa jahiliyah. Saat itu, dalam sebuah perjalanan jauh, ia membawa berhala kecil yang terbuat dari kurma atau tepung sebagai sesembahan darurat. Berhala itu ia perlakukan layaknya tuhan, diletakkan dengan hati-hati dan disembah.
Namun perjalanan itu panjang dan rasa lapar tak tertahankan. Tak ada makanan lain selain berhala yang ia buat sendiri. Maka Umar pun memakan berhala yang ia sembah, sedikit demi sedikit hingga habis. Umar kemudian tertawa ketika menceritakan kisah ini di hadapan Rasulullah dan kaum Muslimin. Ia menertawakan dirinya sendiri atas kebodohan masa lalu. Betapa rapuhnya keyakinan yang dibangun tanpa akal dan nurani.
Humor dalam kisah itu bukan ejekan, melainkan kesadaran. Ia hadir sebagai cermin reflektif. Umar tidak sedang merendahkan agama, tetapi justru menegaskan kekeliruan manusia ketika akal dan iman ditanggalkan. Betapa absurdnya menyembah sesuatu yang pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan manusia, bahkan dari rasa lapar.
Di titik inilah humor dalam tradisi Islam menemukan bentuknya yang khas. Ia tidak selalu berupa lelucon ringan, tetapi juga bisa hadir sebagai ironi yang menyadarkan.
Ada pula kisah yang pernah disampaikan beberapa habaib dan ulama dalam ceramahnya, ketika Umar mengadu kepada Rasulullah karena ada persoalan dengan istrinya. Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang menyendiri, tertawa mendengar keluhan itu. Ketika Umar protes, Rasulullah menjelaskan bahwa beliau pun mengalami hal serupa karena anak dari sahabatnya. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan Hafshah adalah putri Umar. Kata Nabi, “Sesungguhnya apa yang disebutkan Umar itu juga pernah terjadi pada kami.’” Tawa pun pecah, dan ketegangan mencair. Humor menjadi alat penyambung empati antar-manusia, bahkan di antara para manusia mulia.
Humor profetik adalah humor yang berkaitan dengan sifat dan sunnah nabi. Canda dari Nabi membuat pesan berat terasa ringan, membuat kebenaran lebih mudah diingat, dan menciptakan kedekatan emosional antara penyampai pesan dan audiensnya. Rasulullah SAW memahami betul hal ini, jauh sebelum teori komunikasi modern membahasnya.
Dengan demikian, humor dalam tradisi Islam adalah pengejawantahan dari kebijaksanaan. Ia digunakan untuk mendidik tanpa menggurui, menegur tanpa melukai, dan mengingatkan tanpa memaksa. Humor Nabi adalah contoh bagaimana tawa bisa menjadi bahasa kemanusiaan yang paling halus sekaligus paling dalam.
Penutup
Dari Srimulat kita belajar bahwa tawa bisa lahir dari kesederhanaan. Dari stand up comedy kita belajar bahwa humor dapat menjadi kritik sosial yang menggugah kesadaran. Dan dari tradisi Islam kita belajar bahwa humor pun memiliki etika, batas, dan nilai moral.
Pada akhirnya, komedi bukan semata soal lucu atau tidak lucu. Ia adalah soal relasi atau frekuensi. Ketika relasi itu tersambung, frekuensinya sama, humor menjadi jembatan. Sebaliknya, humor bisa juga berubah menjadi jurang lebar antara petutur dan pendengarnya.
Di situlah tawa menemukan maknanya. Ia bukan sekadar bunyi, melainkan bahasa kemanusiaan.**