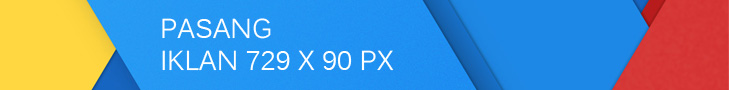Fenomena Kini: Takut Menghadapi Kebenaran
Dr. Asep Dudi Suhardini, M.Ag (Wadek 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba)
DI tengah kemajuan zaman yang ditandai dengan ledakan informasi, keterbukaan data, dan tuntutan transparansi, manusia modern justru memperlihatkan kecenderungan paradoksal: takut menghadapi kebenaran. Kebenaran, yang dalam narasi klasik dianggap sebagai cahaya pembebas, kini sering diposisikan sebagai ancaman yang mengguncang kenyamanan, kestabilan identitas, bahkan keutuhan relasi sosial.
Willful ignorance —sebuah bentuk pengabaian sadar terhadap informasi—adalah pilihan untuk tidak tahu, meskipun tahu itu mungkin dan bahkan penting. Dalam masyarakat modern yang dibanjiri data dan seruan etis, willful ignorance menjadi benteng terakhir bagi mereka yang tidak ingin terganggu oleh beban moral dari pengetahuan. Konsumen yang memilih tidak membaca label produk yang mencantumkan pelanggaran hak buruh, warga yang enggan mengetahui dampak ekologis dari gaya hidup mereka, atau pemimpin yang menolak laporan kerusakan sistem karena takut kehilangan legitimasi, semuanya adalah contoh dari kehendak untuk tetap dalam ketidaktahuan. Sikap ini bukan sekadar kelalaian, melainkan keputusan untuk menghindari tanggung jawab moral yang melekat pada pengetahuan.
Di sisi lain, truth avoidance mencerminkan dimensi psikologis yang lebih lembut namun sama berbahayanya. Ia adalah usaha menghindari kebenaran karena kebenaran itu sendiri dirasa mengancam kestabilan emosional. Seorang anak yang tidak ingin menerima bahwa orang tuanya telah meninggal, individu yang menolak fakta tentang rusaknya hubungan rumah tangga, atau masyarakat yang menghindari diskusi tentang ketimpangan sosial—semuanya sedang mempraktikkan truth avoidance. Di era modern yang menuntut adaptasi cepat dan tekanan tinggi terhadap performa diri, kebenaran kerap dipersepsi bukan sebagai pintu transformasi, melainkan sebagai pemicu krisis eksistensial. Dalam konteks ini, avoidance menjadi mekanisme pertahanan batin, pelindung dari rasa perih, malu, atau kehilangan makna.
Fenomena ini semakin diperparah oleh algoritma digital dan ekosistem media sosial yang memperkuat filter bubbles dan confirmation bias . Dunia maya membentuk cermin bias yang memperkuat persepsi semu dan menghalangi konfrontasi dengan realitas yang tak nyaman. Di sinilah willful ignorance dan truth avoidance menemukan ladang suburnya: bukan hanya sebagai respons individu, tetapi sebagai pola struktural masyarakat yang menghindari refleksi mendalam dan perubahan radikal.
Dalam tataran filosofis, kedua konsep ini adalah cerminan dari krisis keberanian eksistensial. Manusia modern lebih takut pada luka psikologis dari pengetahuan dibanding penderitaan akibat kebodohan. Kebenaran, yang dulu dirayakan dalam tradisi rasional dan religius sebagai jalan keselamatan, kini sering direduksi menjadi gangguan atau bahkan “musuh” bagi ketenangan personal.
Padahal, keberanian untuk menatap kebenaran adalah inti dari kedewasaan moral dan spiritual. Kebenaran, meski menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju pemulihan—baik pada tataran personal maupun kolektif. Dalam dunia yang penuh ilusi, menolak tahu adalah bentuk kebohongan terhadap diri sendiri. Sedangkan menghindari tahu adalah bentuk penundaan luka yang pada akhirnya hanya akan semakin dalam.
Dengan demikian, memahami willful ignorance dan truth avoidance bukan semata soal mengenali kelemahan manusia, melainkan juga membuka jalan menuju kesadaran baru: bahwa keberanian untuk menerima kebenaran, meski pahit, adalah fondasi perubahan yang sejati. Di tengah gemuruh modernitas, barangkali yang paling revolusioner adalah menjadi manusia yang berani tahu, berani merasa, dan berani bertanggung jawab.
Dalam wilayah politik, kebenaran sering kali menjadi komoditas yang dinegosiasikan. Ia tidak lagi diposisikan sebagai fondasi moral kekuasaan, melainkan sebagai alat retoris atau senjata strategis untuk membentuk opini dan mempertahankan legitimasi. Di sinilah willful ignorance dan truth avoidance menjelma menjadi praktik sistemik. Para elite sering kali tahu kenyataan—tentang korupsi internal, kegagalan kebijakan, atau penderitaan rakyat—namun memilih bungkam atau mengelak, karena mengakui kebenaran berarti membuka celah bagi pertanggungjawaban dan perubahan struktur kekuasaan. Sebaliknya, publik yang kecewa atau terpolarisasi, memilih menghindar dari fakta politik yang kompleks dan menyakitkan, lalu bersembunyi dalam kesederhanaan narasi populis atau dogma ideologis yang menenangkan.
Dalam dunia politik modern, kebenaran menjadi barang mahal, bahkan berbahaya. Jurnalis yang mengungkap kebenaran bisa dibungkam, akademisi yang jujur dikucilkan, dan pejabat yang berkata jujur dianggap mengancam stabilitas. Maka yang terjadi bukan demokrasi berbasis kesadaran, tapi pertunjukan besar yang mengelola persepsi. Politik menjadi seni menyembunyikan kenyataan, dan warga menjadi penonton yang, ironisnya, ikut memilih tidak ingin tahu terlalu banyak karena tahu bahwa tahu berarti gelisah, dan gelisah berarti harus bertindak.
Namun, dalam pandangan ajaran agama, kebenaran bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ia adalah amanah ilahiah, cahaya petunjuk yang membebaskan dari kesesatan. Dalam Islam, misalnya, kebenaran (al-ḥaqq) adalah salah satu nama Allah (Asmaul Husna), dan menegakkannya merupakan panggilan moral-spiritual setiap insan beriman. Nabi Muhammad ﷺ pun diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai sosok yang “menyampaikan dengan benar dan tidak menyembunyikan”
ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـٰلَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًۭا
“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.”
(QS. Al-Ahzab: 39)

Ajaran agama tidak memberi ruang bagi kompromi terhadap kebenaran demi kenyamanan, apalagi demi kekuasaan.
Dalam konteks ini, penghindaran terhadap kebenaran adalah bentuk kedurhakaan, bukan hanya terhadap akal, tapi terhadap Allah. Memilih tidak tahu ketika bisa tahu adalah bentuk pengingkaran terhadap potensi fitrah manusia sebagai makhluk pencari makna. Lebih dari itu, agama mengajarkan bahwa keberanian menerima kebenaran, betapapun pahit, adalah tanda keimanan yang hidup:
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًۭا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ
“Dan katakanlah: ‘Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.’ Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka…”
(QS. Al-Kahfi: 29)
Ayat ini bukan mendorong relativisme, melainkan menegaskan bahwa kebenaran itu tetap dan berasal dari Tuhan, meski manusia diberi kebebasan memilih untuk menegakkannya atau menghindarinya. Maka setiap pengabaian terhadap kebenaran, terutama oleh mereka yang memiliki kuasa, adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh-Nya.
Dalam ruang politik dan agama, kebenaran adalah titik temu antara akal dan wahyu, antara tanggung jawab moral dan petunjuk spiritual. Ketika kebenaran dikorbankan demi kepentingan duniawi, maka yang lahir adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasi hakiki, dan umat yang kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kebenaran ditegakkan—meski mengguncang—ia menjadi fondasi bagi tatanan yang adil, manusiawi, dan berpijak pada nilai-nilai ketuhanan.
Dalam dunia yang serba cepat, penuh tekanan citra, dan manipulasi simbol, keberanian menatap kebenaran adalah sikap revolusioner. Di tengah gelombang kebohongan yang dikemas rapi, berpihak pada kebenaran—baik dalam kehidupan pribadi, politik, maupun keberagamaan—adalah jalan sunyi yang mulia.
Willful ignorance dan truth avoidance mungkin terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi hanya akan melahirkan ketidakadilan, disorientasi, dan krisis kemanusiaan yang lebih dalam. Sebaliknya, memilih tahu, meski menyakitkan, adalah langkah pertama menuju tobat kolektif dan transformasi sejati.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 42)
Semoga keberanian untuk melihat dan menerima kebenaran—apa pun risikonya—tetap hidup dalam jiwa-jiwa yang mencari makna, dalam hati para pemimpin yang bertakwa, dan dalam nurani masyarakat yang menghendaki perbaikan. (ADS)