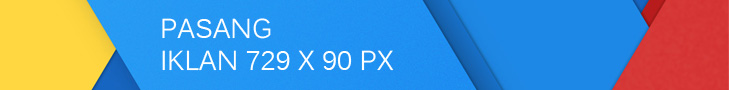Manusia dan Anugerah Penderitaan
Dr. Muhammad E. Fuady (Pengamat Komunikasi - Dosen Fikom Unisba)

“YA ALLAH, selama dua tahun saya tidak pernah lepas salat tahajud. Saya berusaha menjalani ini, kenapa hasilnya seperti begini?” tutur seorang wanita politisi.
Ia sedang bercerita tentang fase gelap dalam hidupnya. Ia ingin lepas dari jeratan hukum, mendekat pada Sang Pencipta, namun putusan pengadilan tak sesuai harapan.
Wanita itu berada di titik terendah kehidupannya. Ia harus menjalani hukuman 12 tahun penjara. Politisi sekaligus figur publik itu merasa kehilangan segalanya. Status sosialnya runtuh, reputasi hancur, batin terguncang. Kehidupan berubah drastis, dari ruang kekuasaan yang gemerlap menuju ruang sempit berjeruji besi.
Di titik itu, ia mengaku kecewa kepada Allah.
Namun justru di balik jeruji itulah ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyebut penjara sebagai jalan yang membuatnya benar-benar mengenal Sang Ilahi.
Di Rutan Pondok Bambu, wanita itu, Angelina Sondakh mendalami agama, belajar mengaji, dan berhasil menghafal 15 juz Al-Qur’an. Ia bahkan menjadi guru mengaji bagi narapidana lainnya. Ruang yang semula terasa sebagai hukuman perlahan berubah menjadi ruang riyadhah, latihan spiritual yang menundukkan ego dan meluruhkan keakuan.
“Penderitaan itu membuat aku mengenal Allah. Aku sampai pada konsep tidak ada kemelekatan. Aku tidak punya apa-apa. Semua ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya sudah. Di situ aku belajar bersyukur. Hidup itu hanya dengan Allah aku bisa menikmatinya.”
Angelina Sondakh merenungi masa lalunya. Ketika menjadi anggota dewan, ia berada dalam fase arogansi dan lupa diri. Kemudahan dan kemewahan membuatnya lalai. Kekuasaan dan privilege, tanpa disadari, menumbuhkan rasa keakuan. Ia merasa memiliki kendali atas hidupnya. Padahal sejatinya ia hanya butiran debu dalam pusaran takdir.
Penderitaan yang semula terasa sebagai hukuman, perlahan berubah menjadi jalan kesadaran. Kehilangan yang semula dianggap ketidakadilan, berubah menjadi ruang perenungan. Dari sinilah kita belajar bahwa tidak semua luka adalah musibah semata. Ada penderitaan yang justru menjadi anugerah.
Allah berfirman :
وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Q.S. Asy-Syura [42]: 30)
Dan dalam ayat lain:
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. At-Taghaabun [64]: 11)
Ayat di atas mengajak kita untuk memaknai peristiwa itu sebagai mekanisme penyucian. Dalam perspektif iman, penderitaan tidak menjadi hukuman, melainkan kasih sayang Allah. Ia menggugurkan dosa, melunakkan hati, dan mengembalikan manusia pada kesadaran paling dasar bahwa ia tidak memiliki apa-apa.
Kisah di atas memberi pelajaran yang lebih luas. Bahkan dalam situasi ketika manusia merasa diawasi oleh sistem, deviasi atau penyimpangan tetap kerap terjadi. Apalagi bila manusia dihadapkan pada situasi tanpa monitoring, ia bisa tergoda untuk mengabaikan hukum dan mengelabui institusi yang mengawasi.
Dalam politik, Lord Acton mengemukakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan cenderung korup, apalagi tanpa pengawasan. Itulah alasan mengapa ada perangkat dan institusi yang menata kelola agar aktivitas kekuasaan tetap berjalan pada koridornya.
Dalam teologi, pengawasan tidak pernah absen. Ada institusi agung yang melakukan pengawasan atas perilaku setiap individu. Raqib dan Atid senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk setiap anak Adam. Ada surga dan neraka sebagai konsekuensi perilaku manusia. Ada Tuhan yang melihat semua gerak-gerik hamba-Nya, bahkan yang tersembunyi sekalipun.
Memang, iman itu adakalanya naik dan turun. Sayangnya, pengetahuan serta keyakinan pada Allah tidak selalu berkorelasi dengan ketundukan dan ketaatan pada perintah dan larangan-Nya. Manusia sering lupa diri, bahkan tak jarang berbangga diri dalam kekeliruannya.
Jika Allah memberi teguran, itu harus disyukuri. Teguran itu bisa hadir dalam bentuk kesulitan, permasalahan, musibah, sakit, atau penderitaan. Dalam tradisi keimanan, sakit dan penderitaan dapat menggugurkan dosa. Ia menjadi sarana penyucian, bukan sekadar hukuman.
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena hal itu” (HR. Bukhari Muslim).
Itu berarti Allah masih menyayangi dan memberi kesempatan untuk kembali. Allah ingin hamba-Nya pulang dan berharap hanya kepada-Nya. Kepada Allah sajalah manusia menggantungkan diri.
Jalan untuk Kembali Pulang
Berbahagialah saat seseorang dapat “menghadirkan” Allah dalam dirinya. Kesadaran bahwa Allah amat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Ia melakukan kebaikan bukan karena berharap surga, dan menjauhi kejahatan bukan karena takut neraka. Semuanya lillah, karena Allah semata.
Sebaliknya, ada kisah tragis. Seorang wanita, sebut saja namanya Dewi Bulan. Orang ini bukan seorang muslim. Ia viral di media sosial karena menantang Allah SWT dan menghina Nabi Muhammad SAW.
“Tahun lalu saya menantang Allah SWT yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini ya, apakah bisa dalam satu bulan bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan, saya tantang kamu Allah SWT,” ucap Dewi Bulan pada 2023.
Kabarnya hingga saat ini wanita tersebut baik-baik saja. Tampaknya tak ada kejadian apa pun yang menimpa dirinya. Memang, beredar video dirinya sedang terbaring menderita di sebuah rumah sakit. Itu video hoax. Beberapa pihak nyatakan ia baik-baik saja.
Lalu mengapa Allah tak memberikan hukuman seperti permintaannya. Justru, saat Allah mengabaikan seseorang, tak menggubris orang tersebut, itu adalah penderitaan paling buruk. Diabaikan oleh Allah, tidak dianggap, tak direspons, itu adalah yang seburuk-buruknya penderitaan. Jangankan didengar, dilirik saja tidak. Itu sangat tragis.
Pada akhirnya, kita sampai pada kesadaran yang paling hakiki bahwa diberi anugerah hidup dan kesempatan mengenal Allah saja sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan di situlah makna terdalam dari penderitaan, itu bukan luka, melainkan jalan untuk kembali pulang.***