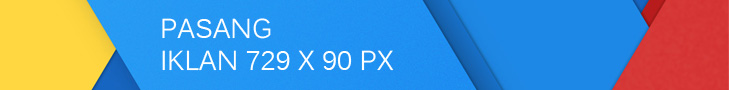Menata Ulang Study Tour: Antara Larangan dan Solusi

Oleh Dr. Ayi Sobarna, M.Pd. (Ketua Program Studi PG PAUD FTK Unisba)
BELAKANGAN, publik di Jawa Barat bahkan hingga ke berbagai provinsi lain tengah ramai membicarakan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah mengadakan kegiatan study tour. Respons masyarakat pun terbelah: ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah kebijakan ini memang langkah terbaik. Benarkah sang gubernur menolak study tour sepenuhnya?
Jika ditelusuri, larangan ini lahir dari niat baik: melindungi siswa dari kegiatan study tour yang bergeser menjadi “piknik berlabel pendidikan”. Banyak yang akhirnya lebih menonjolkan unsur konsumsi daripada pembelajaran. Tak jarang pula memberatkan keuangan orang tua, membuka peluang praktik bisnis tidak sehat, hingga memicu kecemburuan sosial antar siswa.
Namun, kebijakan yang langsung menyapu bersih seluruh bentuk study tour justru berisiko menghilangkan manfaat yang sebenarnya bisa diraih. Faktanya, jika dirancang dengan benar, study tour dapat menjadi bagian penting pendidikan holistik: memperluas wawasan, membangun keterampilan sosial, dan menanamkan nilai kebangsaan secara kontekstual.
Permasalahan utamanya adalah pergeseran tujuan. Kini, banyak study tour yang lebih mirip agenda wisata mewah — menginap di hotel berbintang, berkunjung ke mal, atau menikmati destinasi luar kota — tanpa arah edukasi yang jelas. Dampaknya, nilai pembelajaran memudar, kesenjangan ekonomi antar siswa makin terasa, dan orang tua semakin terbebani. Bahkan, di sejumlah sekolah, kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang kehilangan ruh pendidikannya.
Larangan total jelas bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah penataan. Pemerintah provinsi dapat membuat panduan baku: memilih destinasi edukatif, membatasi biaya, memastikan kegiatan memiliki target pembelajaran yang terukur, dan menyediakan alternatif untuk siswa yang tak dapat ikut.
Dulu, study tour sederhana namun sarat makna. Murid diajak ke museum, pabrik tahu, peternakan, atau pusat seni — langsung menyaksikan proses dan merasakan pengalaman nyata. Kini, orientasinya sering berubah menjadi ajang foto dan belanja, sementara substansi pembelajaran terabaikan.
Bayangkan jika study tour kembali diarahkan ke pengalaman yang autentik: mengunjungi pusat teknologi lokal, berdialog dengan petani organik, atau mempraktikkan pembuatan kerajinan tradisional. Di era Kurikulum Merdeka, ini sejalan dengan pembelajaran berbasis proyek dan konteks nyata.
Di Jawa Barat, ribuan sekolah menggelar study tour tiap tahun dengan nilai total miliaran rupiah. Seperti pisau, ia bisa menjadi alat bermanfaat atau berbahaya, tergantung siapa yang mengelola dan bagaimana pelaksanaannya.
Ada kisah inspiratif dari seorang guru di kabupaten yang mengajak muridnya ke kebun kelor milik warga. Di sana, siswa belajar mengenal tanaman, mengolah hasil panen, hingga membuat minuman herbal. Biaya? Hanya dua puluh ribu rupiah per anak. Tanpa hotel, tanpa bus pariwisata, tapi pulang membawa semangat dan cerita bermakna. Apakah kegiatan seperti ini layak ikut terhapus hanya karena praktik buruk di tempat lain?
Tiga langkah perbaikan yang mendesak dilakukan:
-
Tetapkan standar dan panduan edukatif — pemerintah daerah dapat membuat daftar destinasi belajar, mulai dari UMKM, pesantren produktif, lembaga riset, hingga situs sejarah.
-
Beri ruang kreativitas pada sekolah — tidak semua study tour harus ke luar kota; kegiatan lokal yang sederhana justru bisa lebih berkesan.
-
Bangun sistem pengawasan transparan — libatkan komite sekolah dan orang tua agar kegiatan terhindar dari pungli dan manipulasi.
Jika dikelola bijak, study tour menawarkan manfaat besar:
-
Belajar kontekstual di museum, kebun raya, atau UMKM, sehingga teori menjadi nyata.
-
Memperluas wawasan sosial dengan mengenal budaya baru dan menumbuhkan toleransi.
-
Meningkatkan semangat belajar lewat pengalaman langsung yang memantik rasa ingin tahu.
-
Melatih kemandirian dan tanggung jawab dalam mengatur perlengkapan dan waktu.
-
Menginspirasi karier lewat kunjungan ke dunia kerja yang nyata.
Dengan perencanaan matang, study tour bisa menjadi laboratorium kehidupan yang mendidik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik — tanpa menjadi beban biaya.
Jadi, apakah Gubernur Dedi benar-benar anti study tour? Sejatinya, tidak. Ia menolak praktik yang menyimpang dari tujuan pendidikan. Larangan total bukan jalan terbaik. Menata lebih efektif daripada menghapus. Ibarat petani, solusinya bukan menebang seluruh tanaman saat ada gulma, melainkan mencabut gulma itu agar padi tetap tumbuh.
Dedi Mulyadi dikenal fleksibel; ia pernah merevisi kebijakan penghentian operasional Bandara Husein Sastranegara ketika efek negatifnya lebih besar. Pemimpin sejati tak segan mengubah keputusan demi hasil yang lebih baik. Karena itu, besar kemungkinan ia juga akan mempertimbangkan ulang kebijakan ini jika mendapat masukan konstruktif dari guru, orang tua, dan pihak terkait.
Alih-alih memperdebatkan larangan, mari mencari cara agar study tour kembali membumi: membentuk karakter, memperkaya pengalaman, dan meninggalkan kesan mendalam di hati pelajar. Sebab pendidikan sejati bukan hanya di ruang kelas — ia hidup di perjalanan, di sawah, di pabrik, di museum, dan di dunia nyata yang menanti untuk dieksplorasi.**