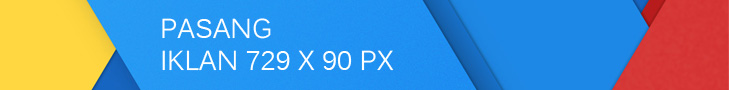Tantangan Keagamaan Pasca-Serangan AS ke Venezuela
Oleh Dr. Muhammad E Fuady (Dosen Fikom Unisba, pengamat komunikasi politik)

PADA fase awal globalisasi informasi, relasi kuasa antarnegara dibangun melalui simbol, wacana, dan citra. Media menjadi instrumen utama untuk membingkai realitas, membentuk opini, serta memengaruhi sikap publik di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, globalisasi informasi tidak sekadar menghadirkan konektivitas, melainkan menjadi arena pertarungan ideologis, politik, dan kultural. Negara-negara kuat tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga narasi, framing, dan produksi makna untuk meneguhkan dominasi.
Namun perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa perang informasi tidak berhenti pada penguasaan wacana. Ia justru berlanjut dan bermetamorfosis menjadi operasi militer terbuka. Ketika opini publik global telah “dipersiapkan” melalui narasi tentang ancaman, krisis, atau dalih kemanusiaan, maka intervensi bersenjata tampil seolah sebagai konsekuensi yang sah, rasional, dan tak terelakkan. Perang tidak lagi diawali oleh peluru, tetapi oleh cerita.
Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela memperlihatkan pola ini secara terang. Alasan resmi yang dikemukakan, mulai dari isu imigran, narcoterrorism, hingga stabilitas kawasan, bekerja sebagai bagian dari perang narasi global. Ia berfungsi sebagai kamuflase moral untuk membenarkan tindakan yang bersifat ekspansionis. Dalam banyak intervensi militer AS, publik menengarai kepentingan utama tetap berkisar pada penguasaan sumber daya strategis. Statement Trump pascaserangan ke Venezuela menegaskan itu.
Pola serupa pernah terjadi di Irak dengan dalih senjata pemusnah massal, serta di Libya atas nama demokratisasi dan perlindungan warga sipil. Semua berawal dari konstruksi ancaman, dan berakhir pada runtuhnya tatanan sebuah negara.
Pada titik ini, globalisasi informasi tidak lagi dapat dipandang netral. Ia berubah menjadi instrumen hegemonik. Ketika narasi tidak lagi cukup efektif, kekerasan militer pun tampil sebagai kelanjutan yang dilegitimasi. Dunia menyaksikan bagaimana bahasa moral dan kemanusiaan digunakan untuk menutup wajah kekuasaan yang agresif.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang ketimpangan global menjadi relevan melampaui konteks keislaman semata. Dalam Globalisasi Dunia (2001), Al-Qaradawi menyoroti relasi internasional yang tidak seimbang, di mana negara kuat mendikte aturan global, sementara negara lemah dipaksa tunduk atas nama stabilitas, demokrasi, dan keamanan internasional. Dunia modern, menurutnya, tidak berjalan di atas prinsip keadilan universal, melainkan dalam logika dominasi dan subordinasi.
Ketidakberimbangan kekuatan ekonomi, politik, dan militer melahirkan relasi global yang timpang. Negara-negara kuat bertindak sebagai penentu kebenaran sekaligus pelaksana hukuman, sementara negara-negara lemah kehilangan ruang yang adil. Dalam kondisi seperti ini, hukum internasional kerap kehilangan makna substantif karena diterapkan secara selektif sesuai kepentingan kekuasaan.
Kasus Venezuela memperlihatkan kritik tersebut secara nyata. Sebuah negara berdaulat dapat ditekan, diancam, bahkan diserang tanpa mandat internasional yang jelas, sementara narasi moral diproduksi secara massif untuk meredam resistensi global. Ketimpangan ini bukan anomali, melainkan konsekuensi dari sistem global yang sejak awal dibangun di atas relasi yang tidak setara.
Dalam situasi seperti ini, komunitas keagamaan dan masyarakat dunia dihadapkan pada tantangan serius. Bagaimana bersikap di tengah dunia yang secara retoris menjunjung hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian, tetapi dalam praktiknya sarat dengan agresi dan ketidakadilan. Sikap kritis tidak identik dengan penolakan terhadap dunia global, melainkan penolakan terhadap normalisasi kekerasan yang dibungkus oleh bahasa moral dan kemanusiaan.
Perang informasi yang berujung pada agresi militer harus dibaca sebagai satu rangkaian utuh. Media bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi bagian dari mekanisme kekuasaan. Perang pun tidak lagi sekadar benturan senjata, melainkan puncak dari proses panjang manipulasi makna dan legitimasi.
Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak ke arah penggunaan kekuasaan yang semakin terbuka dan tanpa rasa malu. Globalisasi informasi yang dahulu digadang sebagai jalan menuju keterbukaan dan dialog kini justru kerap menjadi pendahulu bagi kekerasan bersenjata. Ketimpangan global yang dikritik para pemikir etis dan keagamaan bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang terus berulang dalam bentuk baru.
Dalam konteks ini, umat beragama harus memiliki kejernihan dalam mengamati isu global. Siapapun harus jujur, berpihak pada keadilan, dan menolak dominasi yang mengorbankan kemanusiaan. Agama, pada akhirnya, diuji bukan oleh seberapa indah narasinya, tetapi oleh nurani jernih dan keberanian umatnya berdiri di tengah ketimpangan dan kekerasan oleh negara.
Dalam perspektif teologis, ketika kekuasaan melampaui batas dan kezaliman dipertontonkan, agama menjadi koridor moral. Umat beragama tidak menjadi penonton, ia aktor yang aktif mengkritisi ketimpangan. Keimanan menemukan maknanya bukan hanya di ruang ibadah, juga keberpihakan terhadap yang tertindas, menjaga martabat kemanusiaan sebagai amanah dari Tuhan.
Dibutuhkan solidaritas global lintas bangsa dan agama untuk menolak ketidakadilan struktural. Hari ini Venezuela menjadi contoh nyata, esok lusa hal serupa bisa menimpa negara lain yang diposisikan berseberangan dengan kepentingan negara adidaya. Ketika agresi dinormalisasi melalui dalih keamanan dan kemanusiaan, dunia sesungguhnya sedang kehilangan kepekaan etisnya. Solidaritas global menuntut setiap umat beragama, bangsa, dan negara untuk bersuara, menolak agresi militer yang dikemas dengan narasi moral.
Tantangan keagamaan hari ini bukan pada perbedaan akidah, melainkan pada keberanian menghadapi ketidakadilan global.**