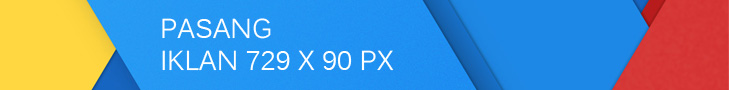Membedah Spritual Complacency
Dr. Asep Dudi Suhardini, M.Ag (Wakil Dekan 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba)

DALAM kehidupan rohani sering muncul keadaan yang tampak seperti ketenangan, padahal pada dasarnya menyimpan kelalaian. Keadaan itu disebut spiritual complacency, yaitu rasa puas diri secara rohani yang membuat seseorang berhenti bertumbuh, berhenti gelisah terhadap kualitas iman, dan berhenti memeriksa batinnya. Ia mirip kolam yang permukaannya tenang, tetapi air di dasarnya keruh. Karena permukaannya tenang, orang merasa semuanya baik-baik saja. Padahal justru di situlah bahaya, sebab ketenangan itu bukan hasil kedalaman spiritual, tetapi hasil dari berhentinya dinamika rohaniah.
Banyak orang mengira bahwa kemapanan lahiriah adalah tanda kedekatan dengan Tuhan. Ada yang merasa bahwa rutinitas beragama sudah cukup menjadi bukti bahwa ia berjalan di jalan yang benar. Namun complacency bekerja dengan cara yang lebih halus: ia membuat seseorang tidak lagi merasakan kebutuhan untuk mendekat kepada Allah. Yang terjadi bukan kedekatan, melainkan jarak yang diselimuti rasa aman palsu. Seseorang mungkin masih berdoa, tetapi doa itu tak lagi menembus apa pun; ia hanya mengulangi kata-kata. Ia mungkin masih ibadah, tetapi ibadah itu tidak lagi menjadi ruang untuk memeriksa diri. Kompas batin berhenti bergerak, tetapi ia tidak menyadarinya.
Spiritual complacency biasanya tumbuh dari pengalaman keberhasilan. Ketika seseorang merasa situasinya stabil, hidupnya cukup, masalah besar tidak ada, atau prestasi tampak baik, ia mulai berpikir bahwa perjalanan rohaninya juga baik. Jiwa yang demikian pelan-pelan melepaskan kewaspadaan. Seperti penjaga yang mengantuk karena merasa daerahnya aman, ia tidak lagi melihat bahwa musuh paling berbahaya justru datang saat penjagaan melemah. Dalam tradisi keislaman, banyak ulama menggambarkan kondisi ini seperti penyakit yang tidak menimbulkan rasa sakit; justru karena tidak sakit, seseorang mengira dirinya sehat.
Al-Qur’an memberi gambaran mengenai manusia yang tertipu oleh keadaan tenang. Dalam surah Al-Hadid dijelaskan bahwa hati yang keras muncul ketika manusia larut terlalu lama dalam kenyamanan dunia dan tidak lagi merasakan getaran ilahi. Ketika hati membatu, ia tidak lagi dapat menangkap teguran. Dalam keadaan seperti ini, complacency menjadi pintu bagi kesombongan halus. Seseorang tidak mengatakan secara eksplisit bahwa dirinya suci, tetapi cara pandangnya, perasaannya, dan keputusannya mulai menunjukkan bahwa ia tidak lagi merasa memerlukan bimbingan.
Untuk memahami bahaya complacency, bayangkan seorang pengemudi malam yang sedang melaju di jalan tol. Karena jalannya lurus dan lampu mobilnya terang, ia mulai merasa aman. Tanpa ia sadari, rasa aman itu berubah menjadi kelengahan. Ia tidak melihat bahwa di kejauhan terdapat tikungan tajam. Ia tidak memperlambat laju mobil, tidak memeriksa petunjuk, dan tidak merasa perlu meningkatkan kewaspadaan. Ketika tikungan itu akhirnya datang, ia terkejut, kehilangan kendali, dan mendapati bahwa semua asumsi aman sebelumnya hanyalah ilusi. Begitulah complacency bekerja dalam spiritualitas: ia membuat manusia tidak melihat bahwa perjalanan hidup bukan jalan lurus tanpa risiko, melainkan jalur panjang yang membutuhkan kesadaran penuh.
Di sisi lain, tradisi sufi mengingatkan bahwa seorang hamba hanya benar-benar hidup ketika ia terus-menerus merasa membutuhkan Allah. Rasa butuh inilah yang menjaga hati tetap hidup. Ketika seseorang berhenti merasa butuh, jiwa menjadi kering. Ia mungkin masih beraktivitas secara religius, tetapi kedalaman batin itu hilang. Ibarat pohon yang tampak hijau, namun akarnya tidak lagi menjangkau air tanah, ia akan layu perlahan tanpa terlihat dari luar. Para sufi memandang complacency sebagai hijab yang lebih tebal daripada dosa, sebab dosa sering kali membuat manusia sadar dan kembali, sementara complacency membuat manusia tidak merasa perlu kembali.
Spiritual complacency juga dapat muncul dalam konteks sosial-keagamaan. Ketika sebuah komunitas merasa bahwa pemahamannya paling benar, paling mapan, atau paling selamat, komunitas itu mulai menutup pintu koreksi. Ia sulit menerima kritik, sulit melihat kerentanan diri, dan lama-lama melahirkan kultur superioritas. Situasi ini pernah menjadi perhatian para ulama klasik yang memperingatkan agar manusia tidak terjebak dalam rasa “cukup secara rohani”, sebab perasaan cukup itulah awal dari stagnasi moral. Di titik tersebut, agama tidak lagi menjadi jalan penyucian diri, tetapi menjadi identitas yang dibanggakan semata.
Namun spiritual complacency bukan penyakit tanpa obat. Ia dapat ditangani melalui kesadaran yang jujur: kesadaran bahwa iman selalu hidup dalam proses. Tidak ada titik akhir bagi kedekatan dengan Tuhan. Yang ada adalah perjalanan panjang yang diwarnai jatuh bangun, terang dan gelap, bangkit dan lelah. Ketika manusia kembali menyadari bahwa ia rentan tersesat, maka ia membuka kembali pintu pertolongan ilahi. Langkah pertama untuk mengatasi complacency adalah mengakui bahwa diri tidak pernah selesai. Iman bukan sertifikat, melainkan perjalanan.
Kesadaran ini membutuhkan latihan: latihan untuk terus memeriksa motivasi, menimbang niat, melihat ke dalam diri tanpa membela diri. Dalam tradisi Islam dikenal tindakan muhasabah, yaitu melihat kembali perjalanan secara jujur, tanpa menyalahkan orang lain dan tanpa ilusi tentang diri sendiri. Muhasabah membuat jiwa kembali peka. Ia seperti meniup debu yang menutup kaca, sehingga cahaya dapat kembali masuk. Dengan muhasabah, seseorang dapat membedakan mana ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah dan mana ketenangan yang hanyalah hasil kelalaian.
Ketika seseorang berhasil keluar dari jebakan complacency, ia merasakan kembali getaran yang dulu mungkin pernah dirasakan: getaran takut kehilangan hidayah, getaran rindu untuk mendekat, dan getaran ingin selalu diperbaiki. Rasa rindu inilah yang menghidupkan jiwa. Dengan demikian manusia kembali merasakan dinamika rohani yang sehat. Ketenangan yang muncul setelah itu bukan lagi ketenangan palsu, melainkan kedamaian yang lahir dari hubungan yang terus dijaga.
Pada akhirnya, spiritual complacency adalah pengingat bahwa musuh terbesar dalam kehidupan rohani bukanlah badai besar yang mengguncang, tetapi keheningan yang membuat manusia tertidur. Untuk tetap hidup secara ruhani, manusia perlu menjaga dirinya dari tidur panjang itu, sekaligus menyadari bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah perjalanan tanpa akhir. Selama manusia mau bergerak, membuka mata batinnya, dan mengakui ketergantungannya kepada Allah, maka ia tidak akan terseret oleh puas diri yang menipu, melainkan berjalan di jalan yang subur dengan kesadaran, kelenturan hati, dan kerendahan diri.
Dalam tradisi keislaman, terdapat satu istilah penting yang berkaitan erat dengan bahaya spiritual complacency, yaitu amani. Kata ini muncul dalam Al-Qur’an, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Di sana, amani merujuk kepada harapan-harapan kosong yang tumbuh dari ilusi, bukan dari kesadaran rohani. Amani adalah keyakinan yang tidak berakar pada usaha, tidak bertumpu pada kedalaman iman, tetapi lahir dari keinginan untuk merasa aman tanpa perlu menjalani proses penyucian diri.
Amani adalah sejenis mimpi rohani yang tidak menuntut perubahan apa pun. Ia memberikan kenyamanan psikologis instan, tetapi merenggut kewaspadaan. Dalam amani, seseorang merasa bahwa kedekatannya dengan Tuhan sudah terjamin, apa pun kondisi hatinya. Ia merasa bahwa amalan sederhana sudah cukup sebagai tiket keselamatan, meski hatinya jauh dari transformasi. Seseorang mungkin berkata kepada dirinya, “Tuhan Maha Pengampun,” padahal kalimat itu ia ucapkan bukan sebagai pengakuan kebutuhan, melainkan sebagai penenang yang memadamkan rasa bersalah. Di titik itu, amani berbeda jauh dari harapan sejati.
Harapan sejati lahir dari perjuangan dan kerendahan hati. Sedangkan amani lahir dari keinginan manusia untuk memaafkan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Amani adalah cara halus manusia untuk membungkus kelalaian dengan kata-kata religi. Ia adalah bantal empuk tempat manusia tidur dengan tenang, sementara api kecil kelalaian menyala di sampingnya.
Jika kita kembali pada ayat Al-Baqarah 78, Al-Qur’an menggambarkan kaum yang larut dalam amani sebagai kaum yang buta huruf. Kebutaan huruf dalam konteks itu bukan sekadar kurangnya kemampuan membaca teks, tetapi ketidakmampuan membaca tanda-tanda Tuhan, membaca pesan kehidupan, dan membaca batin sendiri. Ketika manusia tidak membaca dirinya, ia mudah terperosok ke dalam keyakinan-keyakinan kosong. Ia mengira dirinya selamat hanya karena identitas, tradisi, atau anggapan lama yang tidak lagi ditimbang dengan jujur.
Bayangkan seseorang yang berada di perahu kecil di laut luas. Ia tidak memeriksa arah angin, tidak memperhatikan bintang, dan tidak memperbaiki layar. Ia hanya berkata, “Perahuku pasti akan sampai. Aku bagian dari pelaut yang hebat.” Kalimat itu terdengar meyakinkan, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa laut memerlukan keterampilan, bukan sekadar slogan. Amani bekerja seperti kalimat-kalimat semacam itu: ia memabukkan dengan kepastian palsu.
Para ulama tafsir menekankan bahwa akar kata amani, yaitu tamanna, berkaitan dengan angan-angan yang tidak diwujudkan dalam tindakan. Dalam bahasa spiritual, tamanna adalah impian yang tidak pernah turun menjadi amal. Ia seperti benih yang diletakkan di atas batu; kelihatan seperti bibit kehidupan, tetapi tidak pernah tumbuh. Amani membuat manusia merasa sudah memiliki kebun, padahal yang ia miliki hanya benih yang tidak pernah menyentuh tanah.
Dalam kehidupan beragama, amani sering muncul dalam bentuk-bentuk pernyataan yang terdengar saleh. Seseorang berkata bahwa Allah pasti mencintai dirinya karena ia berasal dari keluarga yang baik; atau bahwa surga sudah dekat karena ia pernah berbuat kebaikan besar; atau bahwa dosa-dosa akan terhapus begitu saja karena ia sering mendengar ceramah tentang kasih sayang Tuhan. Pernyataan tersebut mungkin benar dalam sebagian konteks, tetapi menjadi berbahaya ketika berubah menjadi dalih untuk tidak berubah.
Amani menutup pintu tobat. Ia membuat manusia berkata, “Nanti saja,” atau, “Tuhan tahu niatku,” atau, “Aku tidak seburuk itu.” Padahal perubahan diri memerlukan kedisiplinan rohani, kejujuran batin, dan ketekunan yang tidak bisa ditunda. Sebagaimana kesehatan jasmani tidak dapat dijaga hanya dengan mengingat-ingat pola hidup sehat, kesehatan rohani tidak dapat dijaga hanya dengan mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Ia membutuhkan kerja batin yang terus menerus.
Di sinilah hubungan erat antara amani dan spiritual complacency menjadi jelas. Amani adalah narasi batin yang menopang complacency. Ia adalah alasan-alasan halus yang membuat seseorang merasa tidak perlu bangkit. Ia membuat manusia lupa bahwa iman adalah perjalanan, bukan peristirahatan. Amani menyelimuti kelalaian dengan rasa aman, dan rasa aman itu membuat seseorang kehilangan sensitivitas terhadap hal-hal kecil yang menentukan kualitas keimanan.
Para sufi memperingatkan bahwa amani adalah jebakan paling lembut tetapi paling mematikan dalam spiritualitas. Ia tidak datang dengan kegelisahan, melainkan dengan kenyamanan. Ia tidak masuk melalui pintu kesalahan besar, melainkan melalui pintu kecil tempat manusia merasa baik-baik saja. Dalam kenyamanan itulah manusia berhenti menangis untuk dosanya, berhenti merasa rindu kepada Tuhannya, dan berhenti takut kehilangan hidayah.
Amani yang membungkus complacency menjadikan manusia hidup dalam keheningan batin yang menipu. Tidak ada badai di luar dirinya, tetapi badai dalam dirinya berhenti ia dengar. Tidak ada kekacauan di permukaan hidupnya, tetapi kekacauan maknawi telah lama mengendap. Ia merasa aman, tetapi aman itu rapuh. Ia merasa cukup, tetapi cukup itu kosong.
Ketika manusia akhirnya kembali tersadar—entah melalui peristiwa besar, pukulan nasib, atau cahaya kecil yang tiba-tiba menyala dalam hati—ia akan melihat betapa tipisnya selimut yang selama ini ia anggap hangat. Di saat seperti itu, manusia menyadari bahwa keselamatan sejati bukan berasal dari angan-angan, tetapi dari hubungan yang hidup dengan Tuhan: hubungan yang ditandai kerendahan hati, kejujuran, kerja batin, dan kesiapsiagaan.
Amani dapat dihancurkan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa rahmat Allah luas, tetapi kedekatan dengan-Nya perlu diperjuangkan. Kesadaran bahwa janji ilahi tidak pernah mengingkari hamba, tetapi hamba sering mengingkari dirinya sendiri. Kesadaran bahwa surga bukan hadiah bagi mereka yang menghibur diri, tetapi bagi mereka yang menjaga dirinya tetap hidup secara rohani.
Dengan demikian, pembahasan mengenai amani mengajak manusia menembus ilusi yang paling halus dalam hidup spiritual: ilusi bahwa perjalanan sudah selesai. Padahal justru di saat manusia merasa selesai, saat itulah ia paling rentan tersesat.
Surah Al-Baqarah (2) ayat 78:
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
Di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui Kitab kecuali hanya angan-angan (harapan-harapan kosong), dan mereka tidak lain hanyalah menerka-nerka.
لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
(Balasan Allah) bukanlah menurut angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan karenanya, dan ia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. (Surah An-Nisā’ (4) ayat 123)
إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ
Nama-nama itu hanyalah sebutan-sebutan yang kalian dan nenek moyang kalian mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu bukti pun untuk itu. Mereka hanya mengikuti prasangka dan keinginan hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. (Surah An-Najm (53) ayat 23)
Ya Allah,
Tuhan yang mengenal kami lebih dari cara kami mengenali diri sendiri.
Tuhan yang tidak jauh, tetapi sering tidak kami dekati;
yang tidak pernah menutup pintu, tetapi kerap kami biarkan sepi.
Engkau mengetahui betapa seringnya kami tertidur dalam keyakinan-keyakinan yang meninabobokan.
Keyakinan bahwa Engkau pasti memaklumi kami,
bahwa amalan kecil kami sudah cukup,
bahwa hati kami masih bersih,
padahal sering kali kami hanya menutupi kegelapan batin dengan kalimat-kalimat penghibur.
Ya Allah,
selamatkan kami dari amani, dari angan-angan rohani yang tidak pernah kami wujudkan menjadi perjalanan.
Jauhkan kami dari rasa cukup yang menipu,
dari keyakinan palsu yang membuat kami berhenti memperbaiki diri,
dari kelembutan palsu yang membius,
dan dari kata-kata manis tentang-Mu yang kami ucapkan tanpa kedalaman.
Jadikan hati kami peka terhadap bisikan-Mu yang halus.
Jangan biarkan kami hidup dari klaim,
jangan biarkan kami merasa benar tanpa Engkau membenarkan,
jangan biarkan kami merasa dekat tanpa Engkau mendekatkan.
Ya Allah,
Engkau yang membalikkan hati,
tegakkan hati kami di atas kejujuran.
Jadikan kami takut dengan cara takut yang menuntun kami untuk berubah,
dan jadikan kami berharap dengan cara berharap yang membuat kami bergerak.
Biarkan mata kami menangis bila kami mulai jauh,
biarkan hati kami gelisah bila kami mulai lalai,
dan biarkan langkah kami kembali kepada-Mu meski dengan sisa tenaga yang lemah.
Ya Allah,
pada akhirnya kami ini hanyalah hamba-hamba yang sering salah arah,
yang lebih mudah terpesona oleh kenyamanan daripada kebenaran,
yang lebih cepat merasa aman daripada merasa perlu bimbingan.
Maka tuntunlah kami kepada-Mu sebelum kematian menutup peluang untuk berubah.
Terimalah amal kecil kami meski sedikit,
dan bangkitkan keberanian dalam diri kami untuk memperbaiki yang besar.
Bimbinglah kami menuju iman yang hidup,
bukan iman yang hanya tinggal dalam kata-kata.
Ya Allah,
selamatkan kami dari ilusi yang menipu hati,
dan karuniakan kepada kami kedekatan yang tidak palsu,
kerendahan hati yang tidak dibuat-buat,
dan perjalanan menuju-Mu yang tidak terputus.
Amin. (ADS)